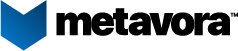Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York menjadi panggung diplomasi yang mendebarkan saat 142 negara menyetujui Deklarasi New York pada September 2025. Dokumen ini bukan sekadar kertas biasa; ia menyerukan gencatan senjata di Gaza, pembebasan sandera, reformasi pemerintahan Palestina tanpa Hamas, dan langkah konkret menuju negara Palestina yang berdaulat berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Hasil konferensi tingkat tinggi yang digagas Prancis dan Arab Saudi pada Juli sebelumnya, deklarasi ini seperti mercusuar harapan di tengah konflik yang telah merenggut puluhan ribu nyawa. Sorak sorai menggema di ruang sidang, tapi di baliknya, dunia terbelah: sebagian melihatnya sebagai kemenangan keadilan, sebagian lain sebagai ancaman stabilitas. Resolusi ini tak memberikan keanggotaan penuh PBB kepada Palestina—veto Dewan Keamanan masih jadi tembok besar—tapi ia memperkuat momentum global untuk solusi dua negara, sesuatu yang telah lama diimpikan namun sulit diwujudkan.
Ruang sidang PBB di New York menjadi saksi ketegangan saat layar menampilkan hasil vote: 142 mendukung, 10 menolak, dan 12 abstain. Mayoritas telak ini mencerminkan pergeseran sikap dunia. Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar berdiri teguh di barisan pendukung, mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober sembari mendorong pengakuan Palestina sebagai imbalannya. Prancis, yang memimpin inisiatif, melalui duta besarnya Jérôme Bonnafont, menyebut deklarasi ini sebagai "peta jalan realistis" untuk perdamaian. Belgia memperkuat posisinya dengan mengumumkan pengakuan resmi Palestina di sidang yang sama, diikuti Australia, Kanada, dan Inggris yang akhirnya bergabung meski sempat ragu. Negara-negara Afrika dan Amerika Latin, seperti Brasil yang telah mengakui Palestina sejak 2010, kembali menegaskan dukungan mereka. Hingga Maret 2025, 147 dari 193 anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara, dan resolusi ini seperti bahan bakar yang mempercepat gelombang itu. Bahkan India, dengan hubungan eratnya ke Israel, memilih abstain alih-alih menolak, menunjukkan sikap hati-hati namun tak sepenuhnya kontra.
Namun, tidak semua pihak bertepuk tangan. Sepuluh negara menolak resolusi, dipimpin oleh Israel dan Amerika Serikat. Duta besar Israel, Danny Danon, menyebut vote ini sebagai "pertunjukan sepihak" yang memberi legitimasi tak langsung kepada Hamas, mengabaikan ancaman keamanan yang dihadapi Israel pasca-serangan 7 Oktober. Negara-negara kecil seperti Mikronesia, Nauru, Palau, Papua Nugini, dan Tonga—sekutu setia AS di Pasifik—turut menolak, kemungkinan karena tekanan diplomatik. Argentina, Paraguay, dan Hongaria di bawah Viktor Orbán, yang dikenal pro-Israel, melengkapi daftar penentang. Sementara itu, 12 negara abstain, termasuk Jerman dan Italia, yang khawatir resolusi ini terlalu terburu-buru. Jerman, misalnya, menekankan perlunya reformasi nyata di Otoritas Palestina sebelum pengakuan penuh, sementara Italia bergulat dengan dinamika politik domestik yang terpecah. Peta dunia ini memperlihatkan jurang yang dalam: mayoritas global condong ke Palestina, tapi kekuatan Barat, terutama AS, tetap pegang kendali di Dewan Keamanan.
Amerika Serikat bereaksi dengan kemarahan yang terukur. Dalam pernyataan resminya, AS menyebut deklarasi ini sebagai "langkah gegabah" yang melemahkan upaya diplomasi untuk gencatan senjata. Sekretaris Luar Negeri Marco Rubio menyoroti bahwa elemen seperti "hak kembali" pengungsi Palestina dalam deklarasi bisa mengancam eksistensi Israel sebagai negara Yahudi. "Ini seperti memberi trofi pada Hamas," kata diplomat Morgan Ortagus, menegaskan bahwa resolusi menciptakan kesetaraan moral yang salah antara Israel dan kelompok militan. AS, yang telah memveto lebih dari 40 resolusi pro-Palestina di Dewan Keamanan sejak 1970-an, menegaskan komitmennya untuk negosiasi langsung yang fokus pada penghancuran Hamas, pembebasan sandera, dan keamanan Israel. Meski menolak keras, Washington tetap menjanjikan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, asalkan ada jaminan bahwa dana tak jatuh ke tangan kelompok bersenjata. Posisi ini mencerminkan dilema AS: di satu sisi, tekanan domestik dari kelompok progresif menuntut sikap lebih lunak ke Palestina; di sisi lain, aliansi strategis dengan Israel tak tergoyahkan.
Uni Eropa menunjukkan wajah yang terpecah namun secara umum mendukung. Prancis memimpin dengan penuh semangat, menyebut deklarasi ini sebagai langkah bersejarah yang bisa membawa reformasi nyata di Palestina dan normalisasi hubungan Israel dengan dunia Arab. Belgia, yang baru mengakui Palestina, menegaskan bahwa ini adalah bagian dari "inisiatif bersama" dengan negara-negara Teluk. Inggris, Kanada, dan Australia, meski bukan bagian UE, ikut mendukung dengan pengakuan mereka sendiri, melihat ini sebagai cara memperbaiki citra di mata Global South. Namun, Jerman dan Italia abstain, mencerminkan kekhawatiran akan dampak pada hubungan dengan Israel. Kanselir Jerman Olaf Scholz menegaskan bahwa pengakuan harus datang setelah pemerintahan Palestina yang kredibel terbentuk, bukan sebagai hadiah politik. Italia, di bawah Giorgia Meloni, khawatir resolusi ini bisa memicu ketegangan di Mediterania. Meski begitu, Komisi Eropa menjanjikan bantuan kemanusiaan tambahan senilai miliaran euro untuk Gaza, sambil mendorong gencatan senjata dan dialog regional. UE tampak berjalan di tali tipis, menyeimbangkan idealisme kemanusiaan dengan pragmatisme geopolitik.
Di sisi Timur, Rusia, Cina, dan Korea Utara menunjukkan solidaritas dengan Palestina, masing-masing dengan agenda sendiri. Rusia, yang sejak era Soviet mendukung Palestina, memilih mendukung resolusi ini sebagai cara menantang dominasi AS di Timur Tengah. Duta besar Rusia Vassily Nebenzia, yang sering gunakan forum PBB untuk kritik kebijakan Barat, melihat deklarasi ini sebagai bukti kegagalan diplomasi AS-Israel. Bagi Moskow, yang tengah sibuk dengan konflik Ukraina, dukungan ini juga alat untuk menarik simpati Global South. Cina, yang mengakui Palestina sejak 1988, memuji deklarasi sebagai "langkah konstruktif" untuk perdamaian. Menteri Luar Negeri Wang Yi menegaskan komitmen Beijing untuk rekonstruksi Gaza, sejalan dengan inisiatif Belt and Road yang ingin perkuat pengaruh di kawasan Arab. Korea Utara, meski tak disebut eksplisit dalam vote, kemungkinan besar mendukung atau abstain—konsisten dengan sikap anti-Israel mereka yang lihat Tel Aviv sebagai sekutu AS. Pyongyang sering gunakan isu Palestina untuk propaganda domestik, menyebutnya sebagai perjuangan melawan imperialisme.
Indonesia, sebagai negara Muslim terbesar dunia, berdiri kokoh di barisan pendukung Palestina. Kementerian Luar Negeri melalui juru bicara Vahd Nabyl A. Mulachela menyambut Deklarasi New York sebagai langkah menuju pengakuan global yang lebih luas. "Palestina berhak atas kedaulatan setara dalam negosiasi damai," ujar Mulachela, menegaskan bahwa Indonesia akan terus galang dukungan untuk gencatan senjata di Gaza melalui forum seperti OKI dan ASEAN. Jakarta tak hanya berbicara; mereka kirim bantuan kemanusiaan, termasuk evakuasi korban luka Gaza untuk perawatan medis, dan tolak keras rencana aneksasi Israel. Posisi ini berakar pada sejarah panjang Indonesia sebagai pendukung anti-kolonialisme, sejak Konferensi Asia-Afrika 1955. Bagi Indonesia, solusi dua negara dengan perbatasan 1967 adalah prinsip tak tergoyahkan, selaras dengan 56 negara OKI yang kompak dorong pengakuan Palestina.
Resolusi ini mencerminkan pergeseran kekuatan global, di mana Global South semakin lantang menentang status quo. Data PBB menunjukkan bahwa sejak status observer Palestina pada 2012, jumlah negara yang mengakui Palestina naik dari 138 menjadi 147, dan deklarasi ini bisa tambah lebih banyak lagi. Namun, tantangan besar tetap ada: veto AS di Dewan Keamanan menghalangi keanggotaan penuh Palestina. Israel khawatir "hak kembali" pengungsi akan mengubah demografi mereka, sementara Hamas mungkin lihat ini sebagai kemenangan simbolis meski dikutuk. Bagi Otoritas Palestina di bawah Mahmoud Abbas, ini adalah amunisi diplomatik, tapi juga tekanan untuk reformasi internal.
Secara ekonomi, deklarasi membuka peluang rekonstruksi Gaza, yang menurut Bank Dunia butuh US$50 miliar. Cina dan UE siap investasi, sementara Indonesia tawarkan bantuan medis dan pendidikan. Namun, tanpa gencatan senjata, semua janji itu seperti menulis di air. Sekjen PBB António Guterres menegaskan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan, tapi dunia harus bergerak cepat. Rusia dan Cina manfaatkan momen ini untuk perkuat aliansi BRICS, sementara Korut gunakan isu ini untuk propaganda. Di Indonesia, resolusi ini menggugah semangat aktivisme muda, dari demo di Jakarta hingga diskusi di forum ASEAN, menunjukkan bahwa isu global ini punya gema lokal.
Deklarasi New York seperti peta yang menjanjikan tujuan damai, tapi jalannya penuh rintangan. Ia mengingatkan bahwa perdamaian butuh lebih dari suara di PBB—ia butuh komitmen nyata, dari bantuan hingga dialog. Di Metavora, kami terus mengajak pembaca untuk terlibat dalam isu dunia seperti ini, karena setiap suara bisa mengubah arah sejarah.
Baca terus artikel-artikel menarik dari Metavora.co, Majalah Digital Indonesia