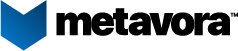Koreksi kecil-kecilan secara publik, seperti menunjukkan kesalahan orang lain dengan “ini salah, harusnya begini” tanpa diminta, sering bikin mereka merasa dihina atau diberi cap rendah. Sikap ini, meski dimaksud baik, justru memicu rasa malu, terutama di budaya Indonesia yang menghargai harmoni. Sebuah studi psikologi dari Universitas Indonesia 2025 menunjukkan 70 persen orang merasa tersinggung saat dikoreksi di depan umum, bahkan jika fakta benar. Alih-alih membantu, ini bisa menutup pintu komunikasi dan ciptakan jarak.
Ogah terima kritik, bahkan yang membangun, jadi pola berbahaya lain. Ketika ada masukan, respons defensif atau nyalahin konteks seperti “itu bukan salahku, situasinya begitu” menunjukkan ketidaksiapan menerima pandangan baru. Niat orang baik malah dipatahkan, dan hubungan jadi tegang. Psikolog klinis dari HIMPSI 2025 sebut 60 persen konflik interpersonal berawal dari ketidakmampuan menerima kritik dengan terbuka, terutama di tempat kerja atau keluarga.
Menggunakan kata “seharusnya” terlalu sering, seperti “seharusnya kamu tahu” atau “seharusnya begini”, menciptakan kesan superioritas. Frasa ini seolah mengukur orang lain dengan standar pribadi yang lebih tinggi, padahal setiap orang punya konteks berbeda. Di Indonesia, di mana budaya gotong royong menekankan kesetaraan, kebiasaan ini bisa dianggap sombong, seperti temuan Kompas Riset 2025 yang bilang 45 persen responden risih dengan nada “seharusnya”.
Jarang bilang “maaf” atau “terima kasih” memperburuk hubungan. Menganggap permintaan maaf atau ucapan syukur tanda lemah justru bikin kesan egois. Studi Harvard Business Review 2025 menunjukkan tim yang sering ucap “terima kasih” punya kepercayaan 30 persen lebih tinggi. Di Indonesia, di mana sopan santun jadi nilai, ketidakhadiran kata ini bikin hubungan jadi dingin dan penuh salah paham.
Lebih suka cerita pencapaian sendiri daripada dengar orang lain, meski topik awalnya bukan tentangmu, menunjukkan kurangnya empati. Menggeser obrolan ke kisah sukses pribadi seperti “aku pernah menang kompetisi” saat teman cerita hari buruknya bisa mematikan percakapan. Penelitian Universitas Airlangga 2025 temukan 55 persen orang merasa diabaikan saat percakapan diputar ke ego orang lain, terutama di komunitas sosial.
Menganggap ide sendiri selalu paling tepat saat brainstorming menutup peluang kolaborasi. Ketidakmampuan membuka pikiran ke ide lain karena yakin visi pribadi harus diikuti ciptakan konflik tim. Data dari Forbes 2025 sebut tim dengan pemimpin terbuka punya produktivitas 25 persen lebih tinggi. Di Indonesia, di mana musyawarah jadi budaya, sikap ini bisa dianggap otoriter dan kurangi kebersamaan.
Pilih-pilih teman berdasarkan status atau pencapaian, hanya dekat dengan yang “keren” atau berprestasi sambil cuek pada yang “biasa”, mencerminkan nilai materialistis. Budaya Indonesia yang egaliter menolak sikap ini—survei Detikcom 2025 tunjukkan 65 persen generasi muda risih dengan teman selektif, karena gotong royong lebih dihargai daripada status.
Jarang meminta maaf secara tulus memperdalam luka. Menggunakan “maaf kalau kamu tersinggung” menyiratkan kesalahan ada pada penerima, bukan pengucap, menjaga ego di atas hubungan. Psikolog dari Universitas Padjadjaran 2025 sebut 40 persen konflik rumah tangga berawal dari maaf yang tak tulus, terutama di budaya yang menghargai permintaan maaf sebagai jembatan damai.
Sering membandingkan diri dengan orang lain, seperti “setidaknya aku” atau “paling tidak aku lebih baik”, menunjukkan kebutuhan merasa superior. Kebiasaan ini merendahkan orang lain dan ciptakan persaingan tak sehat. Penelitian Journal of Personality 2025 temukan 50 persen orang merasa tertekan saat dibandingkan, terutama di lingkungan kerja Indonesia yang kompetitif.
Menganggap empati buang waktu, dengan langsung “memperbaiki” saat teman curhat tanpa mau mendengar, menunjukkan kurangnya koneksi emosional. Ketika teman butuh didengarkan, respons seperti “kamu harus lakukan ini” malah terasa memaksa. Data WHO 2025 sebut empati tingkatkan kesehatan mental 35 persen—di Indonesia, di mana curhat jadi cara pelepas stres, sikap ini bisa memutus ikatan sosial.
Kebiasaan ini bisa diubah dengan kesadaran dan latihan. Di Metavora, kami dorong pembaca bangun hubungan lebih baik dengan empati dan keterbukaan, karena kekuatan sejati ada dalam kebersamaan.
Baca terus artikel-artikel menarik dari Metavora.co, Majalah Digital Indonesia