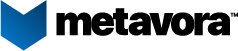Hujan turun perlahan di atas terminal Kampung Rambutan ketika Rani menurunkan kopernya yang mulai kusam di bagian roda. Matanya menatap langit abu-abu Jakarta dengan perasaan yang sulit dijelaskan—antara gugup, takut, dan sedikit harapan. Ia baru tiba dari Yogyakarta setelah menempuh perjalanan delapan jam dengan bus malam. Di tangannya hanya ada satu koper berisi pakaian, map plastik berisi ijazah D3 administrasi perkantoran, dan uang sisa hasil jualan baju online yang tak sampai sejuta rupiah.
Jakarta terasa seperti dunia lain. Suara kendaraan bersahut-sahutan, wajah orang berlalu cepat, semua sibuk, tak ada yang peduli. Di kepalanya hanya satu kalimat yang berputar: “Aku harus bisa.”
Ia menumpang mikrolet menuju daerah Mampang, tempat kos yang direkomendasikan teman lamanya, Nisa. Rumah kos itu berdinding bata cat putih, berada di gang sempit yang basah oleh sisa hujan. Kamar Rani kecil, hanya cukup untuk kasur busa, kipas angin, dan gantungan baju dari kawat. Tapi baginya, tempat itu sudah seperti titik awal menuju masa depan.
Malam pertama di Jakarta, Rani duduk di lantai dengan mie instan dan air galon dalam gelas plastik. Di luar, suara adzan Isya bersahut dari masjid dan musala. Ia menunduk, menatap mie yang mulai dingin, lalu tersenyum kecil.
“Setidaknya aku nggak nyerah di rumah,” gumamnya pelan.
Hari-hari berikutnya berjalan seperti putaran waktu tanpa arah. Rani bangun pagi, membawa map lamaran kerja, berjalan kaki dari satu gedung ke gedung lain. Ia pernah diwawancara di kantor logistik, sempat diterima magang tanpa gaji di perusahaan kecil, bahkan mencoba melamar jadi resepsionis di salon kecantikan. Tapi semuanya berakhir sama: “Kami akan hubungi kamu nanti.”
Uang di dompetnya menipis. Kadang ia hanya makan sekali sehari, kadang menunda makan dengan alasan diet agar tidak malu di depan teman kos.
Nisa, teman lamanya, berbeda. Rambutnya dicat cokelat, kukunya selalu rapi, dan selalu punya uang tunai di dompet. Awalnya Rani tak bertanya dari mana semua itu berasal. Tapi ketika malam-malam Nisa pulang dijemput mobil, dengan parfum mahal yang baunya bertahan sampai pagi, ia mulai curiga.
Suatu malam, Nisa menatap Rani yang sedang menghitung uang receh di atas meja.
“Ran, kamu nggak capek terus-terusan kayak gini?”
“Ya capek, tapi mau gimana lagi.”
“Kalau kamu mau, aku bisa kenalin kamu ke tempat aku kerja. Bukan kerja berat kok, cuma nemenin tamu di lounge. Gajinya bisa jutaan semalam.”
Rani berhenti menghitung. Matanya naik menatap Nisa.
“Lounge? Maksud kamu kayak… tempat hiburan gitu?”
“Ya, tapi aman kok. Nggak harus ngapa-ngapain. Cuma duduk, ngobrol, minum. Yang penting kamu bisa jaga diri.”
Rani diam. Dalam pikirannya, terlintas wajah ibunya di kampung, wajah yang selalu berkata, “Jangan jual harga dirimu demi lapar, Ran. Tuhan nggak tidur.”
Ia hanya menjawab, “Aku pikir-pikir dulu.”
Malam itu, hujan turun lagi. Rani tak bisa tidur. Suara rintik di atap kos seperti irama yang menekan dadanya. Ia menatap HP yang layarnya retak, melihat pesan Nisa: “Kalau berubah pikiran, aku jemput jam 8.”
Pukul delapan lewat lima belas, sebuah mobil hitam berhenti di depan gang. Rani berdiri di balik tirai, menatapnya lama. Lalu, entah karena dorongan keputusasaan atau sekadar ingin melihat, ia keluar.
Di lounge itu, lampu temaram, musik lembut, dan tawa para tamu bercampur dengan aroma alkohol. Rani merasa asing, tapi juga tak punya kekuatan untuk mundur. Ia duduk di pojok bersama Nisa, berusaha menolak pandangan mata-mata nakal yang menilai.
Sampai seorang pria berbadan besar menepuk bahunya.
“Baru ya, Mbak? Sini temenin saya minum.”
Rani menolak halus, tapi tangan pria itu mulai kasar. Nisa menunduk, pura-pura tak melihat. Saat pria itu menarik paksa tangannya, seseorang berdiri di belakangnya.
“Lepaskan.”
Suara itu dalam, tenang, tapi tegas. Seorang pria dengan kemeja hitam berdiri di sana. Tatapannya tajam, seperti menyimpan sesuatu. Pria besar itu sempat menantang, tapi lalu pergi setelah melihat penjaga datang menghampiri.
Rani menatap sosok itu, berusaha mencari kata.
“Terima kasih…”
Pria itu hanya mengangguk.
“Tempat ini bukan buat kamu.”
“Bapak siapa?”
“Cukup tahu kalau aku nggak mau lihat kamu di sini lagi.”
Rani bingung. Pria itu pergi tanpa meninggalkan nama, hanya bayangan punggung yang tegas di antara lampu-lampu lounge.
Malam itu, Rani berlari keluar gedung. Hujan turun deras, membasahi wajahnya bersama air mata yang tak tertahan. Ia berjalan tanpa arah, hingga berhenti di depan gang kos. Pakaian yang ia kenakan sudah basah kuyup, rambutnya menempel di wajah.
Di seberang jalan, sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Dari balik kaca, sosok pria tadi menatapnya — diam, tanpa kata.
Rani tak tahu siapa dia, tapi entah kenapa, dalam keheningan hujan Jakarta, ia merasa seperti ada tangan tak terlihat yang menahan agar ia tidak jatuh terlalu dalam.
Ia melangkah masuk ke gang, lalu berhenti sejenak di bawah lampu jalan.
“Jakarta, aku datang buat hidup, bukan buat mati di dalamnya,” bisiknya pelan.
Dari mobil, pria itu — Rian Hastama — menatap punggung gadis itu yang perlahan menghilang di antara hujan. Ia menyalakan rokok, menatap langit yang sama, dan berbisik,
“Gadis itu… mengingatkanku pada seseorang.”
Lampu mobil menyala, lalu perlahan menjauh di jalan basah Mampang yang sepi.
Dan malam Jakarta tetap tak pernah tidur.
Bersambung ke Part 2 “Antara Harga Diri dan Kesempatan”