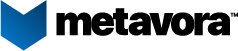Map itu berisi salinan ijazah, fotokopi KTP, dan surat lamaran kerja yang ia tulis semalaman di kamar kos sempitnya di Cipete.Sudah tiga minggu ia melamar ke mana-mana. Toko roti, kafe, butik, hingga perusahaan kecil yang nyaris tidak punya papan nama. Jawabannya selalu sama: “Kami akan hubungi nanti, ya.”
Dan “nanti” itu tidak pernah datang.
Kamar Rani hanya berukuran 3x3 meter. Dindingnya berwarna krem kusam, catnya mengelupas di beberapa bagian. Di pojok kamar ada kipas angin yang bersuara serak seperti perokok tua. Dari jendela, ia bisa melihat atap-atap seng dan mendengar musik dangdut samar dari warung sebelah. Rani duduk di kasur tipis yang sudah kehilangan bentuk, menatap HP-nya yang retak di pojok layar. Notifikasi hanya muncul dari grup WhatsApp keluarga dan grup “Lowongan Jakarta” di Telegram.
Ibunya, yang tinggal di Purwokerto, tadi pagi sempat menelpon.
“Nduk, gimana kerjaannya? Sudah ada panggilan?”
“Belum, Bu. Tapi besok ada wawancara lagi kok,” jawab Rani pelan, menutupi kenyataan bahwa wawancara itu belum tentu ada.
Setelah menutup telepon, Rani termenung lama. Ia tahu ibunya menahan khawatir. Sejak ayahnya meninggal dua tahun lalu karena stroke, kehidupan di rumah makin sulit. Uang tabungan keluarga habis untuk biaya pengobatan dan pemakaman. Rani berjanji pada dirinya sendiri: dia akan berhasil. Atau minimal, tidak pulang dalam keadaan gagal.
Sore itu, setelah wawancara kerja di sebuah butik yang bahkan tak punya AC, Rani berhenti di halte depan Tendean. Jaketnya sudah basah oleh peluh dan matahari sore menampar wajahnya. “Halo Mbak, sendirian aja?” suara seorang perempuan memecah lamunannya. Seorang wanita berusia sekitar 30-an, memakai dress ketat warna merah marun, menghampirinya dengan senyum yang agak mencurigakan. Namanya Mira. Dalam beberapa menit, percakapan yang awalnya ringan berubah jadi aneh. Mira menawarkan pekerjaan di “tempat karaoke eksklusif.”
“Bayarannya besar, Ran. Gak usah takut. Banyak kok yang mulai dari situ, nanti bisa naik kelas.”
Rani diam. Ia tahu maksudnya apa. Mata Mira penuh keyakinan—mungkin karena dia sendiri sudah lama hidup di sisi kota yang gelap itu.
“Aku gak bisa, Kak…”
“Kamu pikir kerja kantoran gampang? Semua orang mau jadi ‘baik-baik’. Tapi hidup di Jakarta gak nunggu orang baik, Sayang. Hidup di sini cuma nunggu siapa yang kuat.”
Rani menatap jalanan macet di depannya. Hatinya tercekat. Ia ingin berteriak, tapi yang keluar hanya desah lelah. Malamnya, hujan turun lagi. Deras. Rani berlari-lari kecil menyusuri trotoar Sudirman, menutupi kepala dengan map lamaran yang kini sudah basah kuyup. Di depan gedung tinggi berlampu biru—tertulis “Hastama Group”—ia terpeleset di genangan air dan jatuh tersungkur. Kertas lamaran pun berhamburan.
“Hei! Kamu gak apa-apa?”
Suara seorang pria terdengar di tengah hujan. Ia memakai jas hitam, menenteng payung besar, dan menunduk menolong Rani. Itulah Rian Wurianta Hastama, anak tunggal pemilik gedung itu. Tapi Rani tidak tahu siapa dia.
“Gak apa-apa, Mas. Cuma jatuh dikit…”
“Kamu nyari kerja ya?” tanya Rian, menatap map yang berceceran.
“Iya, Mas. Tapi udah biasa gak diterima,” jawab Rani dengan senyum pahit.
Rian tersenyum kecil, lalu menawarkan untuk meneduh di lobby. Dalam cahaya lampu gedung, wajah Rani tampak letih tapi tulus.
Ada sesuatu di matanya yang tidak bisa dijelaskan—seperti seseorang yang sudah terlalu sering menelan kecewa, tapi tetap berusaha tersenyum. Rian memperhatikan gadis itu lebih lama dari seharusnya. Malam itu, Rian mengajak Rani minum kopi di kafe kecil dekat Senopati. Awalnya Rani menolak—takut dianggap aneh—tapi hujan belum reda.
“Aku gak biasa nerima ajakan dari orang yang baru kenal, Mas,” kata Rani.
“Tenang aja, aku juga gak biasa ngajak orang yang baru jatuh di depan gedung bapakku,” jawab Rian sambil tertawa kecil.
Tawa itu menular. Rani akhirnya ikut tertawa, meski dalam hatinya masih ada jarak. Mereka berbicara lama. Tentang kerjaan, mimpi, bahkan tentang rasa takut. Rani bercerita bagaimana sulitnya bertahan di Jakarta tanpa kenalan, tanpa uang, tanpa jaminan masa depan. Rian mendengarkan. Tanpa menghakimi. Saat hendak pulang, Rian memberikan kartu namanya.
“Kalau kamu butuh kerja, coba datang aja ke kantor besok. Tapi jangan mikir yang aneh-aneh. Aku serius.”
Rani menatap kartu itu. Di situ tertulis: Rian Wurianta Hastama — Business Development Director, Hastama Group. Dunia seperti berhenti sejenak. Keesokan paginya, Rani berdiri di depan kaca. Dia mematut dirinya—kemeja putih bersih, celana panjang hitam, rambut dikuncir rapi. Wajahnya tampak cemas tapi ada cahaya baru di matanya. Ia menuju kantor Hastama Group. Gedung itu tampak megah dari dekat. Rani gugup, tangannya dingin. Tapi begitu masuk, resepsionis menyambut dengan ramah, dan beberapa karyawan memperhatikannya dengan pandangan penasaran. Rani tidak tahu bahwa langkahnya pagi itu akan mengubah segalanya. Di ruangan kaca lantai 15, Rian sudah menunggunya.
“Selamat pagi, Rani. Aku sudah bilang ke HR. Mulai hari ini, kamu magang di divisi social impact project.”
Rani hampir tidak percaya.
“Tapi, Mas, saya gak punya pengalaman…”
“Yang penting kamu punya niat. Pengalaman bisa dicari nanti.”
Di luar jendela, langit Jakarta membiru untuk pertama kalinya dalam seminggu. Dan di dada Rani, sesuatu bergetar—sebuah perasaan yang lama tak ia rasakan: harapan. Namun, di antara rasa syukur itu, Rani tidak tahu… Bahwa Mira, perempuan yang menawarinya pekerjaan malam itu, ternyata punya hubungan lama dengan seseorang di lingkaran keluarga Hastama. Dan bahwa masa lalu Rani sendiri menyimpan satu rahasia kelam—sesuatu yang, jika terbongkar, bisa menghancurkan segalanya.
Hujan akan datang lagi. Dan kali ini, bukan hanya membasahi Jakarta… Tapi juga membuka lembaran luka yang belum sempat kering. Pagi Jakarta selalu sibuk—udara penuh klakson, ojek daring saling berteriak, dan langit tampak seperti kaca buram yang menahan panas kota. Namun di lantai 15 Hastama Group, suasana terasa berbeda: sunyi, elegan, berbau kopi arabika dan pendingin ruangan yang terlalu dingin. Rani berdiri canggung di depan ruang rapat besar.
Ia mengenakan blazer pinjaman dari teman kosnya, Rara, dan sepatu pantofel yang sudah sedikit sobek di ujung.
Tapi wajahnya tegas, matanya bersinar: ia siap.
“Silakan duduk, Mbak Rani,” kata Maya, HR officer yang memproses magangnya. Di dalam ruangan itu, layar-layar menampilkan data proyek CSR perusahaan—beasiswa, penanaman pohon, pembangunan rumah baca. Rani akan bekerja di bawah supervisi langsung Divisi Social Impact Project, tim yang dipimpin oleh Rian sendiri.
“Kami sedang mengerjakan program pelatihan kerja untuk perempuan muda dari daerah. Rian bilang kamu punya semangat yang sama,” ujar Maya sambil tersenyum.
“Iya, Bu. Saya ingin bantu perempuan seperti saya dulu, yang datang ke Jakarta tanpa arah.”
Kata-kata itu membuat Maya menatapnya lebih lama—seolah melihat sesuatu yang tulus, langka di antara ruangan kaca dan ambisi para profesional muda itu.
Hari-hari pertama berjalan lambat tapi hangat. Rani belajar mengetik proposal, menyusun laporan, dan menyalin data. Ia selalu datang lebih pagi dari semua orang. Kadang ia menatap langit Jakarta dari jendela besar lantai 15—melihat kota yang dulu menakutkan kini tampak seperti mimpi yang bisa digapai. Rian sering menghampirinya di ruang kerja.
“Kamu kelihatan serius banget. Gak capek?”
“Capek sih, tapi senang. Ini pertama kalinya saya ngerasa berarti.”
“Berarti kamu memang cocok di sini,” ujar Rian sambil tersenyum kecil.
Ada sesuatu di cara Rian menatap Rani: lembut tapi berjarak. Sebuah perhatian yang tidak bisa ia sembunyikan, tapi juga tidak bisa ia jelaskan. Beberapa rekan kantor mulai memperhatikan kedekatan mereka. Bisik-bisik di pantry mulai terdengar:
“Katanya anak magang itu dekat sama Pak Rian.”
“Ah, paling juga modus. Mana ada bos serius sama anak magang?”
Rani pura-pura tidak mendengar. Tapi malamnya, saat berbaring di kasur kos, kata-kata itu menempel di pikirannya. Ia takut dianggap memanfaatkan Rian, padahal ia hanya ingin bekerja, bukan mencari belas kasihan.
Suatu sore, ketika semua orang sudah pulang, Rani masih duduk di depan komputer. Ia sedang menulis draft proposal tentang program pemberdayaan perempuan miskin perkotaan. Ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal.
“Halo?”
“Rani… ini aku, Mira.”
Suara itu langsung membuat napasnya berhenti sesaat. Suara yang dulu menawarkan “pekerjaan” di tempat karaoke.
“Kamu sibuk ya sekarang? Denger-denger udah kerja di perusahaan besar.”
“Kamu tahu dari mana?”
“Jakarta kecil, Sayang. Lagian, aku juga punya kenalan di situ… di Hastama Group.”
Rani terdiam.
“Apa maksudmu?”
“Oh, kamu belum tahu ya? Aku dulu pernah deket sama—ah, nanti aja deh. Nanti kamu tahu sendiri.”
Sambungan terputus. Rani menatap layar ponselnya lama sekali, merasa seolah bayangan gelap dari masa lalu kembali menempel di tengkuknya.
Bersambung ke Part 3. “Darah yang Sama, Cinta yang Salah”