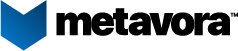Malam itu, stadion El Campín di Bogotá bergelora. Ribuan penggemar Guns N’ Roses datang dari berbagai penjuru ibu kota Kolombia, siap merasakan energi rock klasik. Ketika gitar mulai meraung dan suara drum menggema, suasana sudah cukup magis. Namun konser itu tidak hanya tentang irama dan melodi. Ada detik di mana musik berhenti—untuk sebuah pernyataan.
Saat memainkan lagu Civil War, Axl Rose menahan sejenak—kemudian mengulurkan tangan dan menurunkan sebuah bendera Palestina di tengah panggung. Lampu sorot menyoroti kain yang berkibar itu, lalu ia membungkusnya di tubuhnya sebelum melambungkannya ke udara di antara sorak penonton. Simbol itu mengejutkan banyak orang yang hadir, sekaligus mengundang tepuk tangan meriah dan reaksi global.
Gitaris Slash, tak mau ketinggalan, mengambil bendera dari salah satu penonton dan membentangkannya ke hadapan penonton di atas panggung. Di layar besar stadion, kata “I DON’T NEED YOUR CIVIL WAR” terlihat jelas—merujuk pada lirik lagu yang tengah dimainkan. Momen ini tidak hanya viral secara daring, tetapi juga menggetarkan banyak pihak: penggemar musik, aktivis, dan masyarakat yang melihatnya sebagai sinyal solidaritas.
Lantas, apa yang mendorong Axl Rose melakukan aksi ini? Simbol seperti ini dalam konteks konser bukan sekadar tontonan dramatis. Bagi sejumlah musisi, panggung telah lama menjadi ruang ekspresi politik dan sosial—dari Bob Dylan hingga U2. Dengan mengangkat bendera Palestina, Axl Rose menyisipkan pesannya ke dalam konteks besar konflik global, menjadikan konser rock sebagai medium protes damai.
Namun reaksi tak selalu seragam. Di media sosial, banyak yang memuji keberanian dan konsistensi Axl Rose dalam bersuara untuk keadilan. Di sisi lain, tak sedikit yang mempertanyakan apakah musik dan hiburan harus “diseret” ke ranah politik. Ada yang melihatnya sebagai gestur yang berisiko, bisa memicu kontroversi atau bahkan boikot dari penonton yang berbeda pandangan.
Menilik konteks Kolombia sendiri, negara ini memiliki sejarah konflik internal dan sensitivitas terhadap isu luar negeri. Aksi semacam itu dalam konser besar bisa menimbulkan resonansi lokal: sebagian penonton mungkin terbawa empati terhadap Palestina, sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai campur tangan dalam urusan asing. Namun secara netral, peristiwa ini menegaskan bahwa musik bisa menyentuh tidak hanya telinga, tetapi nurani.
Garis waktu peristiwa ini juga penting dicatat. Konser berlangsung pada tanggal 7 Oktober 2025 di Estadio El Campín. Pada waktu itu, konflik antara Israel dan Palestina tengah menjadi perhatian global dengan eskalasi kemanusiaan yang menyedot sorotan media internasional. Banyak seniman dan tokoh menggunakan kerangka budaya untuk ikut bersuara—dan Guns N’ Roses ikut bergabung dalam gelombang itu.
Dalam lanskap musik dunia, langkah seperti yang diambil Axl Rose bukanlah yang pertama, tetapi tetap langka bagi band rock klasik dengan jangkauan massa luas. Ia menegaskan bahwa posisi publik seseorang—apalagi seniman—dapat dipakai untuk menyampaikan pesan perdamaian atau solidaritas, lebih dari sekadar hiburan semata.
Walaupun demikian, ada tantangan praktis: interaksi antara hiburan dan politik sering dihadapkan pada respons hukum, media, bahkan tekanan dari pihak promotor atau otoritas lokal. Namun sejauh ini, belum ada kabar resmi tentang sanksi atau protes masif terhadap Guns N’ Roses di Bogotá khusus karena aksi itu. Publikasi berita lebih banyak menyoroti aspek viral dan artinya di mata dunia.
Bagaimana reaksi penonton? Dari video dan laporan liputan, penonton merespons dengan sorak sorai, tepuk tangan, dan euforia—seolah mereka menjadi saksi momen istimewa, bukan sekadar konser biasa. Mereka menyadari, malam itu bukan hanya tentang lagu-lagu rock, tetapi tentang simbol dan makna yang lebih luas.
Secara lebih luas, kejadian ini memperlihatkan bagaimana era digital memicu penyebaran cepat momen-momen seperti ini ke seluruh dunia. Dalam hitungan jam, video Axl Rose dengan bendera Palestina menyebar ke media sosial, diberitakan oleh outlet musik dan berita utama, dan memicu diskusi lintas negara.
Bagi Metavora, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa budaya populer dan politik selalu berpotongan. Musik tidak pernah semata hiburan; ia bisa menjadi alat suara, tanda keprihatinan, atau panggilan solidaritas. Sebagai platform majalah digital, Metavora akan terus menyajikan liputan yang menggabungkan estetika seni dan kepedulian sosial, serta mendorong pembaca untuk melihat musik bukan sekadar suara, tetapi medium perubahan.
Baca terus artikel-artikel menarik dari Metavora.co, Majalah Digital Indonesia